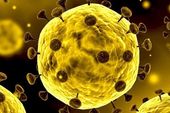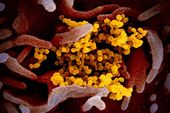Escape Velocity, Meninggalkan Mental Puas Diri

Lemparkan sesuatu ke atas, ia akan jatuh lagi. Pesawat terbang tinggi, akan mendarat di muka bumi. Kita semua terikat sangat erat oleh kekuatan maha besar yang benama gravitasi tadi.
Kecepatannya akan berkurang secara perlahan oleh tarikan gravitasi bumi. Tapi ia masih akan cukup cepat untuk mencapai suatu titik di mana gravitasi bumi tidak lagi cukup kuat untuk menariknya kembali ke muka bumi.
Ia akan terbebas dari pengaruh gravitasi, melayang bebas di ruang angkasa. Dalam fisika kecepatan itu disebut kecepatan kabur, atau escape velocity.
Bahan bakar itu dibakar secara bertahap, diubah menjadi tenaga gerak yang dikeluarkan terus menerus, hingga titik gravitasi nol dicapai. Itulah yang dilakukan oleh para astronot.
Sains dan teknologi kita masih tertinggal jauh, bahkan masih tertinggal bila sekedar dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang sedang berkembang.
Cara berpikir kita, cara hidup kita, semangat dan etos kerja kita masih rendah. Lebih parah lagi, kita korup. Kita masih terbelakang.
Tidak hanya dalam tingkat pendidikan, tapi juga dalam hal kemakmuran. Emak dan Ayah memulai hidup dari sebuah gubuk di tepi hutan saat mereka mulai membangun kebun. Saat mereka tua, mereka sudah jauh lebih makmur.
Kami memulai hidup dengan tingkat kemakmuran yang Ayah dan Emak punyai, dan melanjutkan hidup lebih makmur lagi.
Tentu saja ada pula yang menurun. Orang tuanya makmur dan berpendidikan, anak-anaknya jauh di bawah taraf itu. Yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak orang-orang yang meningkat, dan mencegah orang-orang untuk menurun.
Apa yang sedang terjadi? Korea adalah orang yang sedang mendaki. Mereka sedang bersemangat. Adapun Jepang, mereka sudah di puncak. Orang-orang yang sekarang membangun Jepang adalah generasi yang dibesarkan dalam lingkungan puncak. Mereka bukan para pendaki.
Lalu anak-anak kita menjadi anak-anak malas, yang di kemudian hari tidak tahu mereka akan hidup menjadi apa. Jadilah mereka generasi gagal. Gagal untuk sekedar mengulangi sukses orang tuanya.
Kalau ini terjadi secara massal, bangsa kita akan jadi roket gagal. Terbang sejenak, lalu jatuh tak berdaya, terhempas hancur di muka bumi. Kita jadi negara gagal.
Jangan pernah puas dengan pencapaian kita sekarang. Jangan merasa hebat. Jangan cepat-cepat jumawa, ingin terkenal, ingin dipuja dengan kontribusi kecil kita saat ini. Masih banyak yang harus kita kerjakan sebelum kita mati 20 atau 30 tahun lagi.
Tentu saja anak-anak saya tidak harus jadi doktor. Tapi mereka harus bisa berkontribusi jauh lebih besar dari yang sudah dan akan saya lakukan. Demikian pula anak-anak Anda semua.
Sama halnya, kita tidak perlu menjalani hidup miskin agar anak-anak kita jadi pejuang tangguh. Kita hanya perlu menghindari hal-hal yang bersifat memanjakan, dan memberikan mereka hal-hal yang menumbuhkan semangat.
Detilnya tidak bisa saya tulis dalam tulisan singkat ini. Tapi intinya, masa depan bangsa ini di mulai dari rumah kita masing-masing.
Kita bukan sekedar hamba-hamba perut yang bekerja untuk sekedar mengisi perut kita sehari-hari. Kita adalah mesin-mesin roket pendorong, yang harus membebaskan bangsa ini dari tarikan gravitasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
Bangunlah setiap pagi dengan semangat itu!
Tulisan Hasanudin Abdurakhman lain bisa dibaca juga di http://abdurakhman.com