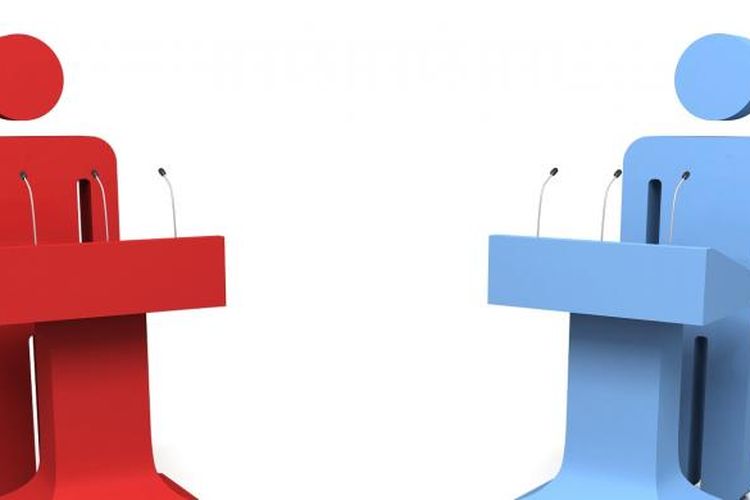Cara Meladeni Debat di Media Sosial
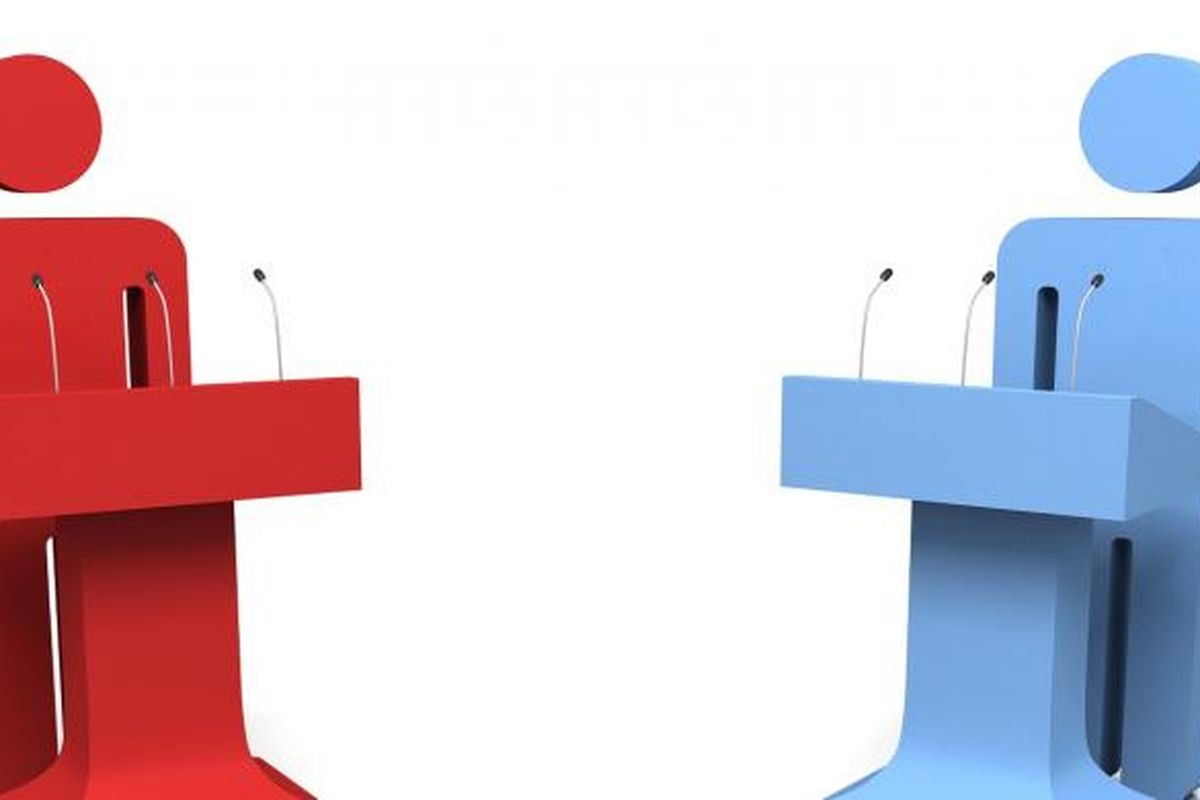
KOMPAS.com - Tahun politik adalah "tahun panas". Dan nampaknya semenjak pemilihan gubernur DKI, setiap tahun menjadi tahun politik. Perdebatan di sosial media selalu panas, namun tidak pernah sepanas bulan-bulan belakangan menjelang pemilihan presiden.
Kata-kata konfrontatif seperti "goblok", "bakar", "bangsat", "sontoloyo", "tolol", "bajingan", "bunuh", dan lain-lain membanjir lini masa sosial media kita. Bahkan hewan yang tak bersalah sama sekali seperti anjing dan babi,terseret-seret mulut dan jempol manusia yang tidak bisa menahan nafsu marahnya di status-status dan komentar-komentar.
Siapapun terlibat mulai anak sekolah sampai profesor, dari guru sekolah sampai anggota DPR. Pria, wanita, besar, kecil, miskin, kaya, pengangguran, pensiunan, artis, mantan artis, karyawan, wiraswasta, ASN, dosen, semuanya seperti tersihir keajaiban Whatsapp, Twitter, Instagram, dan Facebook untuk menumpahkan sumpah serapahnya. Tentu saja termasuk saya.
Isu agama mudah bangkitkan emosi
Harus diakui, sulit untuk tidak terprovokasi status-status bersliweran setiap detik. Jempol ini selalu bernafsu komentar, berdebat dan berkelahi. Karena berkelahi di sosial media tidak punya konsekuensi fisik, tidak perlu melihat wajah marah lawan debat.
Berbeda kalau debat beneran, atau berkelahi beneran. Seperti provokator yang saya jumpai hari Kamis minggu yang lalu. Orang tidak punya nyali pun seperti singa atau harimau di dinding facebook.
Begitu ditantang ngobrol langsung tiba-tiba bungkam. Situasi semacam ini dengan gampang ditunggangi para petualang politik yang menghalalkan segala cara demi kursi kekuasaan.
Mulai dari isu PKI, segala macam hoax, dan yang terakhir pembakaran bendera. Kenapa hampir semua isu terkait agama? Karena isu ini sensitif dan paling mudah membangkitkan emosi.
Eksploitasi identitas kelompok
Cherian George, dalam bukunya “Hate Spin” atau diterjemahkan menjadi Pelintiran Kebencian menegaskan “penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan,dan digunakan sebagai strategi politik yang mengeksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan.”
Nampaknya cara-cara demikian ada kemiripan dengan yang terjadi di Indonesia. Agen-agen kebencian diciptakan, buzzer-buzzer politik bermunculan dengan nilai kontrak ratusan juta.
Itu benar terjadi sekarang, di sekitar kita. Ketika akun-akun palsu, agak palsu, maupun yang asli di sosial media menebarkan tautan-tautan provokasi. Mereka para buzzer berpesta. Sementara korbannya berkelahi satu sama lain, saling membenci satu sama lain.
Lalu bagaimana menghentikannya? Menegakkan keadilan? Keadilan tidak akan tegak hanya dengan mengkoarkan status. Menurut saya, tidak usah berharap dengan sesuatu di luar diri kita.
Mulai dari diri sendiri
Harus mulai dari diri sendiri, harus mulai dari hal-hal sederhana, yang kecil-kecil kalau kata Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. Penulis "Seven Habits of Highly Effective People", Stephen Covey menyarankan mengubah situasi, harus mulai dari hal yang bisa kita pengaruhi, alias mulai dari diri sendiri.
Menurut Michael Mascolo, profesor psikologi dari Merrimack College, Massachusetts, Amerika Serikat. Kebencian tidak dapat dipadamkan dengan kebencian yang lain. Api tidak akan dapat padam dengan mengobarkan api yang lain.
Jadi, bagaimana sebaiknya menanggapi provokasi? Pertama lihat dulu siapa memprovokasi. Tidak ada gunanya menanggapi akun abal-abal, misalnya akun Facebook isinya melulu tautan ujaran kebencian.
Hanya memiliki “friends” sangat minim. Bisa jadi itu akun kloning yang digunakan buzzer politik memviralkan isu. Ketika sudah yakin akun yang kita ajak ngobrol bukan akun palsu, punya pemilik benar-benar ada, baru obrolan bisa dilanjutkan.
Ajang debat kusir
Seperti ilustrasi di bawah ini :
Bona (bukan nama sebenarnya): Sebenarnya sangat disayangkan ada aksi pembakaran bendera itu. Banser salah. Tapi tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Mereka membakar bendera organisasi terlarang yang diacung-acungkan di depan hidung mereka.
Tentu kita berharap kasusnya akan segera jelas, pihak berwajib juga sudah mengamankan pelakunya. Hati-hati, ini isu sensitif jangan mau diadu domba.
Rong-Rong (juga bukan nama sebenarnya): Lho, kamu itu gimana? HTI tidak punya bendera. Itu bendera tauhid! Mereka melecehkan Islam! Kemana Banser ketika kami membela ulama? Mereka kebanyakan malah menjaga tempat ibadah agama lain! Update informasi dong, jangan sok netral!
Rong-rong merespon dengan emosional, tidak dalam konteks yang sesuai dengan yang disampaikan Bona. Justru menyerang pendapat Bona yang dengan gegabah dianggap “membela” Banser. Obrolan kemudian menjadi tidak efektif dan berpotensi menjadi ajang debat kusir. Rong-rong menekankan pemikiran “kami versus mereka”.
Otak berhenti berpikir kritis
Menurut Prof. Mascolo, serangan personal semacam ini merusak inti diskusi yang ingin dibangun Bona, bahkan menuding Bona tidak peduli dengan agamanya sendiri. Tentu saja hal ini bisa memprovokasi Bona dan melupakan bangunan diskusi yang ingin dibangun di awal.
Bona: Justru HTI yang membajak kalimat tauhid dalam benderanya, seperti juga ISIS, Al-Nusra, mereka mensponsori pemberontakan di Suriah, di Irak, di Yaman. Yang ada hanya kehancuran. Makanya banyakin baca dong! Jangan cuma baca link ga jelas!
Pada titik ini, diskusi sebenarnya sudah tidak ada gunanya. Serangan personal membuat individu semakin defensif, semakin emosional. Ketika itu terjadi. otak berhenti berpikir kritis, yang berfungsi adalah amygdala.
Amygdala adalah bagian otak paling primitif, yang pola pikirnya adalah flight (lari) atau fight (berantem) ketika menghadapi ancaman. Seperti otak rusa atau zebra yang melihat predator.
Menang tanpa menyakiti
Kita harus menghadapi kebencian dengan kemauan untuk melihat kenapa seseorang membenci sesuatu, apa motifnya. Untuk menuju ke sana tidak bisa dilakukan tanpa menjaga hubungan personal. Misalnya dengan menawarkan sebuah pertanyaan terbuka.
Bona: Sebenarnya sangat disayangkan ada aksi pembakaran bendera itu. Banser salah. Tapi menurutku tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Mungkin kamu punya pendapat lain. Bagaimana menurutmu Rong-rong? Apakah ada cara supaya kita tidak diadu domba?
Kita bisa perhatikan, materi ingin disampaikan Bona sebenarnya sama, tapi caranya berbeda. Bona menanyakan pada Rong-rong dengan memposisikan sebagai orang sejajar. Tidak lebih tahu.
Dari sana diharapkan Bona lebih tahu apa yang dipikirkan Rong-rong. Meski keduanya tidak saling setuju. Tapi setidaknya keduanya setuju untuk tidak saling setuju. Sehingga diskusi tidak terperosok menjadi konflik tidak perlu.
Dalam istilah jawa “menang tanpa ngasorake”. Menjadi pemenang dengan tidak membuat orang lain merasa kalah. Istilah keren yang mungkin mendekati adalah win-win solution. Selamat berdiskusi.
Sumber :
Czopp, A. M., Monteith, M. J., & Mark, A. Y. (2006). Standing Up for a Change: Reducing Bias Through Interpersonal Confrontation. Journal of Personality & Social Psychology, 90, 784-803
Mascolo, M. F. (2016). The Transformation of a White Supremacist: A Dialectical-Developmental Analysis. Qualitative Psychology, 1-20.