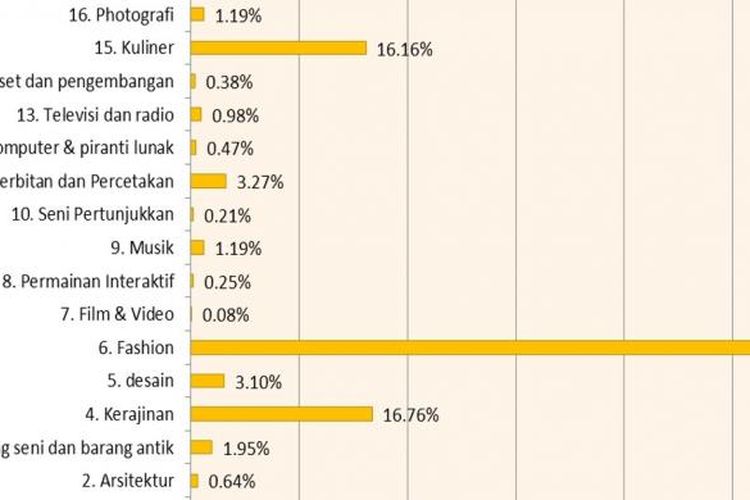Lulusan Ilmu Komunikasi, Mau Dibawa ke Mana?

Bagaimana melihat kondisi umpama jamur di musim hujan, ketika nyaris seluruh perguruan tinggi di Indonesia mutakhir menghadirkan fakultas/program studi/jurusan ilmu komunikasi? Apakah ini surplus, ataukah defisit, dengan kebutuhan riil di lapangan?
Jika memang defisit, kenapa faktanya para ahli komunikasi publik kampiun, sebut di televisi nasional tak selalu jurusan ilmu komunikasi --sebut saja Tina Talisa yang berlatar pendidikan dokter gigi, atau Pemred Kompas TV Rosiana Silalahi yang alumni Sastra Jepang.
Sebelum menjawab prolog pertanyaan tersebut, ada dua baseline yang harus difahami bersama. Pertama, ilmu komunikasi pada dasarnya adalah derivatif dari fakultas ilmu sosial politik di berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini.
Secara historis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik --dengan mother of skills-nya ilmu hukum-- adalah bidang ilmu yang sudah eksis sejak zaman Belanda. Bahkan, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang dibuka dengan seputaran ilmu sosial tersebut.
Karenanya, sebagai sebuah ilmu turunan, ilmu komunikasi menjadi sebuah cabang ilmu relatif baru, dalam proses in making, serta masih butuh dayungan ilmu atas aras zaman agar menjadi salah satu cabang ilmu yang mapan dan kontributif.
Kedua, ilmu komunikasi adalah bidang ilmu inklusif; Siapapun bisa menjadi pelaku profesinya sekalipun berasal dari jurusan tak berkaitan. Hal yang membedakan misalnya dengan profesi pengacara, jaksa, dan hakim yang hanya bisa oleh lulusan sarjana hukum.
Saking cairnya bidang ini, muncul sebutan IPB sebagai Institut Publisistik/Penyiaran Bogor karena banyaknya lulusan kampus agribisnis tersebut kemudian berprofesi sebagai praktisi komunikasi massa handal dan berpengalaman.
Secara praktis, terutama di bidang profesi media massa, kondisi ini wajar saja jika mengingat rubrikasi di media massa sangat beragam. Dari mulai ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, hingga olahraga, yang kemudian menjadi relevan bagi latar ilmu yang majemuk.
Nah, ini tambah menarik, ketika ada proses sertifikasi terkait, semisal uji kompetensi wartawan (UKW), Dewan Pers pun tidak melihat latar pendidikan peserta. Selama diizinkan kantor dan lulus materi UKW terkait kewartawanan, peserta dari disiplin ilmu apapun bisa meraihnya.
Dengan dua titik pijak tersebut, maka dengan sendirinya, lulusan ilmu komunikasi akan masuk bursa kerja maha ketat. Mereka tak bersaing hanya dengan sesama jurusannya, mereka tiada kena sortir pelamar yang ketat dan ekslusif sedari awal.
Maka itu, mengacu pengalaman penulis, tak jarang kemudian lowongan ilmu komunikasi pun "direbut" yang bukan alumni linear. Sering pula terjadi, alumnus ilmu komunikasi yang tak punya keahlian spesifik, dengan mudah dilibas lulusan non komunikasi yang otodidak namun gaul dengan keahlian komunikasinya.
Lalu, jika merujuk kebutuhan riil di lapangan, variabel yang bisa digunakan sebetulnya banyak. Tapi kita lakukan pendekatan paling sederhana dulu, semisal kebutuhan lulusan ilmu komunikasi di Jawa Barat dengan merujuk tingkat keterbacaan koran.
Sebagai media konvensional senior di provinsi ini, dalam catatan penulis, total oplah seluruh koran sekitar 450.000 s.d 500.000 koran/hari. Jika diasumsikan satu koran dibaca tiga orang, maka tirasnya mencapai 1,5 juta-an.
Jumlah penduduk Jawa Barat sendiri akhir tahun 2016 mencapai 47 juta, dengan usia produktif sekitar 65% diantaranya (30 juta), sehingga penetrasi keterbacaan adalah masing-masing mencapai 3,191% dari total penduduk serta 5% dari usia produktif.
Artinya, tingkat utilitas sekaligus peluang pasarnya relatif sangat kecil. Ditambah budaya baru membaca media massa ke arah media baru/new media, maka terjadi posisi begini: Alumni ikom bersaing sangat ketat untuk pasar (konvensional) yang cenderung terbatas!