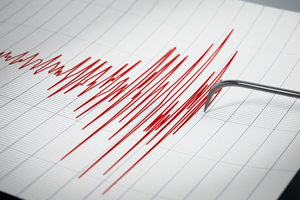Pendidikan Asingkan Budaya Bernalar
Oleh Iwan Pranoto
Dalam pembangunan republik ini, sejak 1970-an pendidikan kerap dianggap kemewahan, bukan kebutuhan. Penyediaan pendidikan bermutu dinomorduakan dibanding penguatan ekonomi. Kebijakan seperti ini berbahaya.
Budaya pendidikan dunia memodelkan pembangunan berdasarkan intelektualitas. Karena sumber daya alam terbatas serta jagat semesta rentan terhadap gangguan, pembangunan berkelanjutan perlu berpusat pada intelektualitas. Implikasi dari model ini, masyarakat belajar serta budaya belajarnya yang tumbuh mengakar jadi penggerak utama pembangunan setiap negara.
Suka atau tidak, pendidikan merupakan lokomotif terdepan pembangunan. Kesejahteraan bangsa serta kekokohan ekonomi bergantung mutlak pada pendidikan. Ekonomi kokoh dapat dicapai jika pendidikan kuat.
Penerapan model ini butuh prasyarat: tujuan pendidikan negara harus dirumuskan dengan akurat. Kecakapan yang diperkirakan dibutuhkan di masa depan harus dikenali dan dianalisis. Dari sana kemudian dibuat standar pendidikan. Oleh karena itu, pertanyaan utama dan pertama yang mutlak dikaji pemimpin negara adalah: ”Kecakapan strategis apa yang perlu dibelajarkan?”
Kecakapan abad ke-21
Di pengujung abad ke-20, dua peneliti—Richard J Murnane (Harvard Kennedy School) dan Frank Levy (MIT)—melakukan riset bersama guna menjawab pertanyaan di atas. Murnane (pakar kebijakan pendidikan) dan Levy (pakar ekonomi urban) mengkaji kecenderungan jenis kecakapan yang kian dibutuhkan dan tak dibutuhkan dunia kerja.
Berdasarkan data tahun 1969-1998, mereka mengungkapkan bahwa kecakapan memecahkan masalah tak rutin dan kecakapan berkomunikasi kompleks semakin dibutuhkan. Pada saat komputer serta teknologi informasi semakin berdaya, banyak masalah rutin dapat dipecahkan oleh mesin. Sebaliknya, manusia justru semakin dibutuhkan pada pemecahan masalah tidak rutin. Kecakapan kedua yang juga semakin dibutuhkan adalah kecakapan berkomunikasi kompleks, seperti kecakapan seorang manajer dalam memotivasi stafnya.
Hal yang paling drastis menurun kebutuhannya adalah kecakapan kognitif rutin. Kecakapan seperti menghafal serta kecakapan berpikir tingkat rendah semakin tak diperlukan.
Berdasar penelitian itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan Programme for International Student Assessment (PISA) guna menjawab pertanyaan: ”Seberapa siap pelajar di dunia di akhir masa wajib sekolahnya, yakni umur 15, untuk menguasai kecakapan abad ke-21?”
Untuk Indonesia, hasilnya memang buruk. Ini dapat dibaca di situs OECD. Mengapa pelajar kita begitu buruk pencapaiannya di PISA? Kita pasti sepakat anak-anak kita tidak bodoh. Lalu, mengapa hasilnya buruk?
Jawabnya sederhana. Anak- anak kita telah ditunjukkan arah belajar kecakapan yang salah. Analoginya, anak-anak kita seperti dibekali kompas yang rusak untuk berpetualang. Mereka dibuat fokus mengejar kecakapan kedaluwarsa, seperti kognitif rutin itu. Sebaliknya, anak-anak kita sangat jarang diberi kesempatan mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti bernalar tingkat tinggi.
Insentif bagi pelajar yang berhasil mengembangkan kecakapan modern tersebut justru nyaris tak terdengar. Bukan maksud tulisan ini mengatakan bernalar tingkat rendah tak diperlukan lagi, tapi harus ada keseimbangan antara kecakapan bernalar tingkat rendah dan tingkat tinggi.
Sampai kini sangat sulit meyakini adanya upaya serius dan sistematis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menindaklanjuti hasil PISA guna meningkatkan pencapaian dua kecakapan tadi. Rangkaian kebijakan pendidikan nasional yang dicanangkan justru kerap bertolak belakang dengan upaya penguasaan dua kecakapan itu.
Budaya belajar