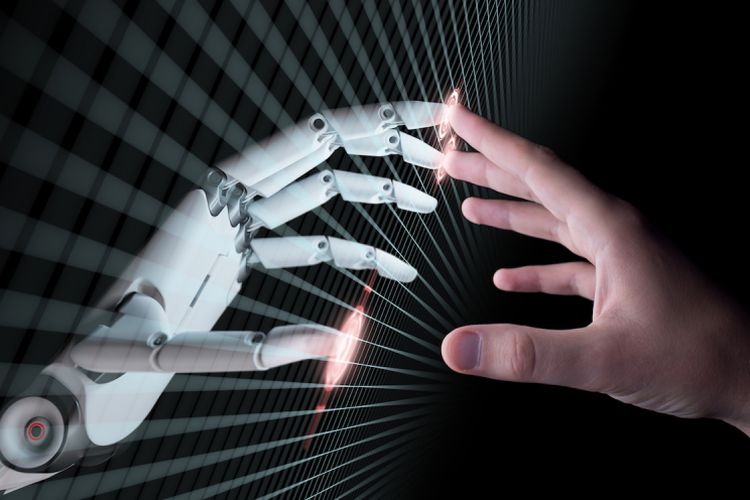Futurismo, Bisakah Kita Percaya pada Kecerdasan Buatan?
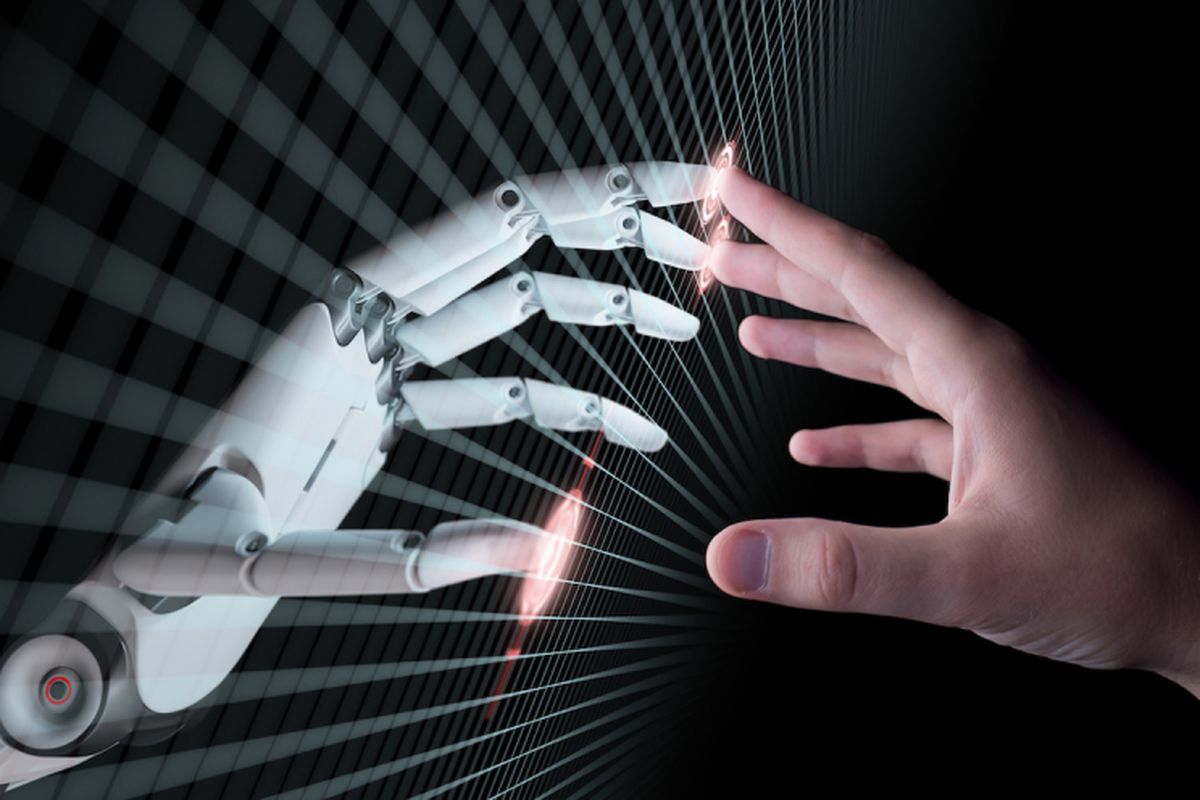
KOMPAS.com - Tentu saja bisa. AI (artificial intelligence) memang ber-evolusi. Tapi bukankah inteligensia serta kebijaksanaan kita juga ber-evolusi? Oh, Tidak?
Tunggu dulu. Berbicara soal AI itu luas sekali: AI yang mana? Anda harus benar-benar memikirkannya sampai anda paham apa yang anda ‘serahkan’ (baca: surender) pada sebuah algoritma AI dalam produk tertentu untuk membantu anda menjalani hidup sehari-hari, baik sebagai profesional di kantor, sebagai pribadi di asosiasi dan komunitas, bahkan sebagai bagian dari keluarga di rumah tangga anda.
Mari saya bercerita sejenak.
Dulu sutradara besar Stephen Spielberg menyuguhkan tontonan luar biasa futuristik melalui film A.I. (2001).
Dalam film itu saya selalu memikirkannya begini, apakah Spielberg terlalu lebay memasukkan unsur emosi ke dalam manusia buatan (humanoid) di dalam film itu?
Kebimbangan itu bertahan untuk waktu yang cukup lama, apalagi dalam berbagai kesempatan saya menontonnya beberapa kali lagi melalui TV Cable di tahun-tahun setelah itu.
Tak lama kemudian tayanglah film-film serupa seperti Ex Machina (2014), Chappie (2015) dan Ghost in The Shell (2017).
Tema keempat film itu adalah konsepsi inteligensia buatan yang sangat masuk akal untuk disebut “coming soon” dalam dunia nyata sehari-hari kita pada waktu itu.
Ada sebuah proses dinamika emosi - yang ‘being exercised’ - oleh mesin-mesin cerdas itu, seolah mereka memiliki kesadaran sendiri akan siapa atau apa mereka; bukan manusia, tapi mereka memiliki kesadaran bebas.
Setahun setelah peluncuran film Ghost in The Shell (2017) yang dibintangi si cantik Scarlett Johansson, saya kumpulkan berita-berita yang muncul sebagai serial studi yang lebih serius namun membumi tentang AI.
Berita-berita itu tayang dalam sekuens yang menurut saya ‘bukan kebetulan’ membahas misteri teknologi AI ini. Semua berita itu muncul di pertengahan tahun 2018, dan semuanya terkait dengan sains.
AI adalah ‘barang serius’
BBC melalui Technology Report yang disampaikan oleh Marianne Lehnis pada pertengahan Juni 2018 mengajak masyarakat mempertanyakan sekali lagi, apakah sebenarnya masyarakat pemakai teknologi AI ingin tahu bagaimana cara mesin AI bekerja dan membuat sebuah ‘keputusan’, ataukah mereka tidak peduli bagaimana algoritma mesin AI bekerja sampai menghasilkan suatu output (keputusan, rekomendasi, angka-angka, dan lain lain)?
Sebulan setelah itu, di pertengahan Juli 2018, portal AdWeek melalui analisisnya, Ben Lamm, memaparkan bagaimana program komputer yang diperkuat mesin AI telah secara efektif dan efisien memberikan rekomendasi serta mengelola penjualan serta aktivitas pemasaran di berbagai perusahaan di dunia.
Dengan kata lain, AI telah secara ‘sukarela’ diterima sebagai pemberi saran atau rekomendasi yang lebih baik ketimbang maestro penjualan sekalipun.
Dalam paparannya, AI ternyata lebih berhasil membangun interaksi dengan konsumen dimana konsumen memang benar-benar ingin didengarkan, dipahami serta dihargai. Akurasi analisis yang dikerjakan mesin AI (misal melalui CRM) jauh lebih tinggi, dan mendapatkan feedback yang sangat positif dari pasar.
Lucunya, tak ada yang mempertanyakan (baca: kepo), bagaimana sebuah algoritma digital bisa melakukan ke semuanya itu dengan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang bila dilakukan oleh satu team salesman terbaik sekalipun.
Mereka – para konsumen itu – lebih suka terima jadi tanpa memusingkan cara kerja ‘jeroan otak’ mesin-mesin AI itu.
Dua bulan kemudian, di pertengahan September 2018, analis di TechGenix, Rahul Sharma yang menyimpulkan bahwa AI, sebagai sebuah bauran antara otomasi (automation) dan kecerdasan (intelligence), telah secara efektif membuat konsumen bergerak menjalani kesehariannya dalam mode ‘autopilot’, dan ini adalah sebuah kenyamanan yang bisa menetralisir rasa ingin tahu bagaimana sih sebenarnya cara AI bekerja.
Fenomenanya sama: tak ada yang benar-benar kepo untuk tahu bagaimana AI bekerja sampai sebuah rekomendasi atau jawaban dikonstruksikan.
Sebenarnya dalam hal sederhana di keseharian saya pun ‘kenyamanan’ di atas juga menina-bobokkan saya untuk tak kritis lagi dalam bernalar, misalnya, mengapa ayam goreng yang kita beli di gerai makanan cepat saji terkenal lebih enak rasanya daripada kalau kita menggoreng sendiri di rumah.
Saya – dan mungkin konsumen yang lain – tak terlalu peduli untuk menanyakan apa sih resepnya, kok ayam goreng di gerai itu lebih sedap rasanya.
Rahul Sharma, Ben Lamm dan juga Marianne Lehnis mewakili manusia-manusia langka yang mencoba kritis terhadap perkembangan teknologi AI yang masuk sangat dalam di berbagai aspek kehidupan kita.
Dan tiba-tiba saya juga ikut kepo.
Apalagi menurut Rahul Sharma, di awal tahun 2020 ini diperkirakan hampir 85 persen interaksi layanan konsumen di perusahaan-perusahaan mapan adalah layanan otomasi, di mana teknologi AI dengan mudah akan mengambil peran besar di sana.
Artinya, saya dan juga para pembaca akan lebih banyak ‘ngobrol’ dengan mesin AI ketimbang manusia.
Apakah preferensi tentang siapa kita dikendalikan oleh AI?
Pertanyaan besar Lehnis, bisakah kita menyerahkan proses pengambilan keputusan pada algoritma mesin AI?
Misalnya begini, kita sedang mengajukan kredit ke bank, semua dokumen elektronik telah kita siapkan lengkap, dan semuanya bagus, dengan kata lain tak ada alasan pengajuan pinjaman kredit kita bakal ditolak.
Namun takdir yang dibentuk mesin AI berkata lain. Pengajuan kredit ditolak. Saat kita tanya apa masalahnya, jawabannya: algoritma credit risk assessment-nya memilih untuk tak mengabulkan pengajuan kredit kita.
Dan celakanya, tak ada satu staff pun di bank yang bisa menjelaskan ‘algoritma’ itu kepada kita. Semuanya diputuskan oleh sebuah mesin AI. Inilah ‘takdir digital’ yang diciptakan algoritma dalam mesin AI.
Atau contoh lainnya – bayangkan anda mengajukan aplikasi visa secara elektronik untuk mengunjungi sebuah negara maju di Barat.
Seperti sudah lazim diketahui, divisi konsuler di kedutaan atau konsulat di negara-negara maju memakai assessment berlapis, termasuk melihat semua akun sosmed kita.
Akhirnya, berdasarkan asesmen ke semua sosmed kita, algoritma mesin AI memutuskan menolak aplikasi visa kita, padahal selama ini dengan mekanisme lama tanpa AI kita sudah keliling dunia tanpa kena masalah penolakan visa. Salah siapa?
Di satu sisi, peran AI sangat besar dalam mempercepat lahirnya jawaban ataupun rekomendasi-rekomendasi terkait bisnis kita, kesehatan kita, rencana perjalanan kita, bahkan tak lama lagi dunia olah raga dan para atlit pun sudah bisa merasakan dahsyatnya peran AI dalam ‘men-training’ mereka menghadapi calon lawan.
Beberapa pialang saham bahkan sudah sangat tergantung pada rekomendasi mesin AI dalam bots mereka: saham apa yang layak mereka beli, kapan dan di angka berapa.
Meski begitu, AI memiliki kontradiksi sendiri bagi sebagian situasi dan kondisi kita. Seperti contoh di atas, tiba-tiba saja eksistensi kita dan karakteristik seperti apa kita ditentukan oleh rumus-rumus yang mungkin tak pernah kita pahami.
Menunggu AI menjadi lebih ‘human-friendly’?
Tak ada yang tahu persis kapan sebaiknya kita menunggu sampai AI benar-benar bisa diandalkan untuk segala hal terkait kehidupan dan aktivitas keseharian kita.
Belum lama ini pabrikan pesawat Airbus merilis hasil uji coba pesawat mereka take-off dan landing dengan dikendalikan sepenuhnya oleh AI.
Pilot, ko-pilot dan teknisi berada di kokpit hanya untuk berjaga-jaga bila sistem AI gagal. Kapan – menurut hemat para pembaca – kita benar-benar bersedia menyerahkan kendali kokpit sepenuhnya pada AI? Musuhnya tak hanya sistem malfunction, tetapi yang lebih sangar lagi, gravitasi!
Jadi, kapan kita benar-benar bisa menyerahkan penerbangan kita kepada algoritma AI? Masihkah kita ingat kepada Elaine Herzberg – yang mungkin tak pernah tahu apa yang menghantamnya saat menuntun sepedanya menyeberang jalan empat lajur di Tempe, Arizona di bulan Maret 2018?
Sebuah mobil autonomous Uber dalam mode uji coba self-drive dengan seorang sopir duduk di belakang kemudi menghantamnya yang sekaligus membunuhnya malam itu.
Diberitakan bahwa sistem object recognition Uber gagal secara presisi mengidentifikasi objek yang melintas di depannya, dan sangat terlambat bagi sopir untuk melakukan override (pengambil-alihan kendali) ke kemudi manual.
Sejak insiden itu, uji coba Uber yang dimulai sejak tahun 2016 pada akhirnya dihentikan. Saya yakin apa yang menimpa Uber ini menjadi bahan pembelajaran serius para pegiat autonomus cars dan AI engineer.
Semoga – seperti harapan khalayak banyak yang tak pernah ‘kepo’ bagaimana AI melakukan pekerjaannya – suatu hari nanti AI benar-benar more-human rather than more-machine, dan dapat kita andalkan dalam membantu menjalani peziarahan hidup di dunia ini dengan lebih baik.
Semper Fi!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.