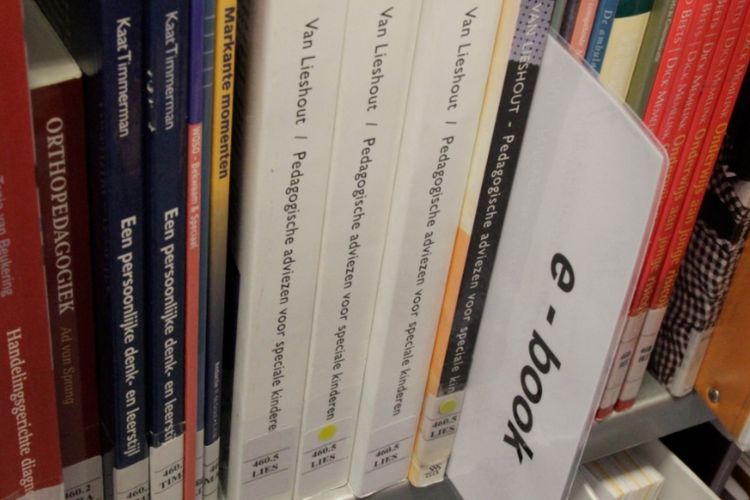Bangsa yang Berkarakter adalah Bangsa yang Membaca

KOMPAS.com - Pada zaman Hindia Belanda, para pelajar di Algemene Middelbare School (AMS) yang setara dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) sekarang diwajibkan untuk membaca. Siswa diminta melahap paling tidak 20 sampai 25 buku karya sastra selama tiga tahun masa studi mereka.
Kegiatan membaca biasanya diikuti dengan menulis karangan setiap minggunya. Dapat dibayangkan banyaknya tulisan yang dihasillkan oleh setiap pelajar selama kurun waktu tiga tahun tersebut.
Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, dan Ali Sosroamidjoyo adalah produk pendidikan tersebut. Sejarah juga mencatat banyak buku dan tulisan dahsyat dari para tokoh itu yang kemudian mengubah nasib bangsa ini.
Sebutlah Di Bawah Bendera Revolusi karangan Soekarno. Buku ini berisi semua pemikiran brilian sang proklamator, terutama pada masa pra-kemerdekaan.
Juga bung Hatta, si kutu buku, yang dengan pledoi terkenalnya “Indonesie Vrij” – Indonesia Merdeka. Hatta menulis itu dari balik tembok penjara di Belanda saat ditahan Pemerintah Hindia Belanda pada masa studinya.
 Suasana perpustakaan di APU, Jepang.
Suasana perpustakaan di APU, Jepang.
Situasi yang ada sekarang sangat berbeda. Sastrawan Taufik Ismail pernah melakukan riset tentang kewajiban membaca buku sastra di beberapa negara di kalangan pelajar setingkat SMU selama tiga tahun masa studi mereka.
Hasil risetnya menunjukkan, para pelajar SMU di Jerman wajib membaca 32 buku sastra, di Belanda 30 buku, di Amerika Serikat sebanyak 25 buku, di Jepang 12 buku, di Singapura 6 buku, di Malaysia 6 buku, dan di Indonesia nol!
Hal itu sudah berlangsung lebih dari 60 tahun dan tidak ada yang "panik". Tragedi nol buku! Suatu kemunduran yang mengerikan.
Lalu, apa hubungannya dengan situasi bangsa? Apakah berarti kita ingin menjadikan semua anak di negeri ini menjadi sastrawan? Bukannya negeri ini konon membutuhkan lebih banyak insinyur, ahli hukum, dan tenaga medis?
Membaca bukan sekedar untuk mengerti arti kata, arti kalimat dan jalan cerita sebuah kisah. Membaca yang benar bukan sekedar kegiatan kognitif. Membaca bukan sekedar untuk ngerti dansekedar tahu. Membaca itu untuk mengolah rasa, mengasah kepekaan, serta membangkitkan kesadaran.
JK Rowling, salah satu penulis tersukses abad ini, mengatakan bahwa salah satu buku favoritnya adalah Macbeth karya pujangga terkenal Willian Shakespeare. Selain itu, Rowling juga menggilai buku-buku politik tentang Abraham Lincoln.
Genre buku yang ditulis Rowling sangat berbeda dengan karya besar Shakespeare. Kita pun sulit membayangkan irisan antara Harry Potter, si karakter utama di buku karangannya dengan Abraham Lincoln si bapak bangsa Amerika, jika kita hanya melihat dari permukaan saja.
Namun, itulah kekuatan membaca! Tak ada batasan genre dalam buku, tidak ada batasan ideologi dalam buku, tidak ada batasan zaman dalam buku.
Membaca novel Harry Potter sama nilainya dengan membaca Little Women karya Louisa May Alcott atau Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk karya Hamka atau Filosofi Kopi milik Dewi Lestari.