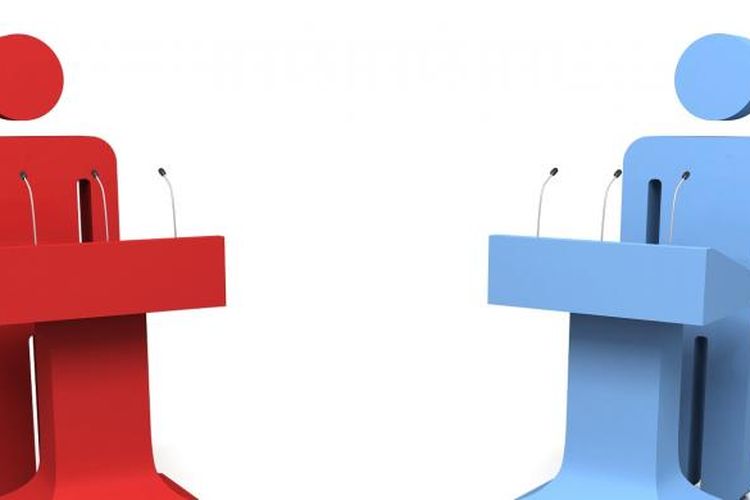Cara Meladeni Debat di Media Sosial
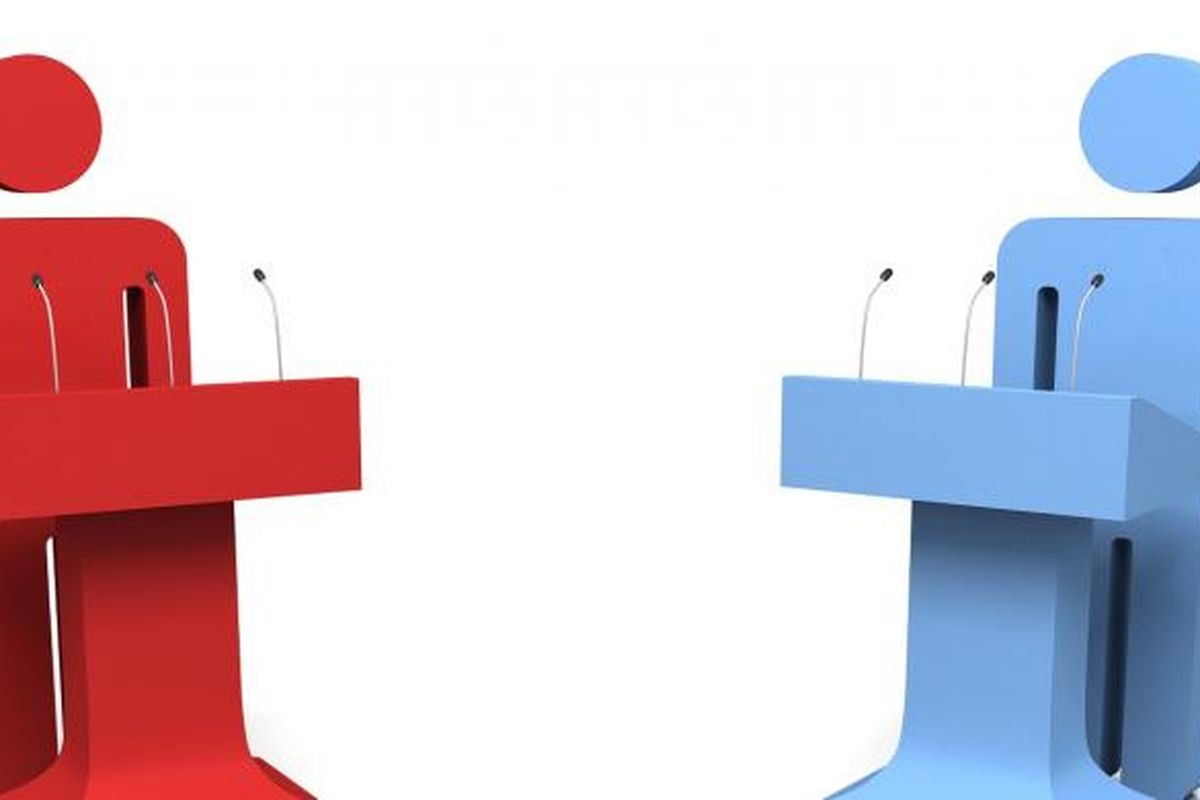
KOMPAS.com - Tahun politik adalah "tahun panas". Dan nampaknya semenjak pemilihan gubernur DKI, setiap tahun menjadi tahun politik. Perdebatan di sosial media selalu panas, namun tidak pernah sepanas bulan-bulan belakangan menjelang pemilihan presiden.
Kata-kata konfrontatif seperti "goblok", "bakar", "bangsat", "sontoloyo", "tolol", "bajingan", "bunuh", dan lain-lain membanjir lini masa sosial media kita. Bahkan hewan yang tak bersalah sama sekali seperti anjing dan babi,terseret-seret mulut dan jempol manusia yang tidak bisa menahan nafsu marahnya di status-status dan komentar-komentar.
Siapapun terlibat mulai anak sekolah sampai profesor, dari guru sekolah sampai anggota DPR. Pria, wanita, besar, kecil, miskin, kaya, pengangguran, pensiunan, artis, mantan artis, karyawan, wiraswasta, ASN, dosen, semuanya seperti tersihir keajaiban Whatsapp, Twitter, Instagram, dan Facebook untuk menumpahkan sumpah serapahnya. Tentu saja termasuk saya.
Isu agama mudah bangkitkan emosi
Harus diakui, sulit untuk tidak terprovokasi status-status bersliweran setiap detik. Jempol ini selalu bernafsu komentar, berdebat dan berkelahi. Karena berkelahi di sosial media tidak punya konsekuensi fisik, tidak perlu melihat wajah marah lawan debat.
Berbeda kalau debat beneran, atau berkelahi beneran. Seperti provokator yang saya jumpai hari Kamis minggu yang lalu. Orang tidak punya nyali pun seperti singa atau harimau di dinding facebook.
Begitu ditantang ngobrol langsung tiba-tiba bungkam. Situasi semacam ini dengan gampang ditunggangi para petualang politik yang menghalalkan segala cara demi kursi kekuasaan.
Mulai dari isu PKI, segala macam hoax, dan yang terakhir pembakaran bendera. Kenapa hampir semua isu terkait agama? Karena isu ini sensitif dan paling mudah membangkitkan emosi.
Eksploitasi identitas kelompok
Cherian George, dalam bukunya “Hate Spin” atau diterjemahkan menjadi Pelintiran Kebencian menegaskan “penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan,dan digunakan sebagai strategi politik yang mengeksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan.”
Nampaknya cara-cara demikian ada kemiripan dengan yang terjadi di Indonesia. Agen-agen kebencian diciptakan, buzzer-buzzer politik bermunculan dengan nilai kontrak ratusan juta.
Itu benar terjadi sekarang, di sekitar kita. Ketika akun-akun palsu, agak palsu, maupun yang asli di sosial media menebarkan tautan-tautan provokasi. Mereka para buzzer berpesta. Sementara korbannya berkelahi satu sama lain, saling membenci satu sama lain.
Lalu bagaimana menghentikannya? Menegakkan keadilan? Keadilan tidak akan tegak hanya dengan mengkoarkan status. Menurut saya, tidak usah berharap dengan sesuatu di luar diri kita.
Mulai dari diri sendiri
Harus mulai dari diri sendiri, harus mulai dari hal-hal sederhana, yang kecil-kecil kalau kata Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. Penulis "Seven Habits of Highly Effective People", Stephen Covey menyarankan mengubah situasi, harus mulai dari hal yang bisa kita pengaruhi, alias mulai dari diri sendiri.
Menurut Michael Mascolo, profesor psikologi dari Merrimack College, Massachusetts, Amerika Serikat. Kebencian tidak dapat dipadamkan dengan kebencian yang lain. Api tidak akan dapat padam dengan mengobarkan api yang lain.
Jadi, bagaimana sebaiknya menanggapi provokasi? Pertama lihat dulu siapa memprovokasi. Tidak ada gunanya menanggapi akun abal-abal, misalnya akun Facebook isinya melulu tautan ujaran kebencian.