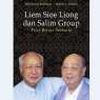"Laut Bercerita" yang Bikin Merinding

KOMPAS.com - Setelah hampir tiga bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat. Hitam. Kelam.
Selama tiga bulan mataku dibebat kain apak yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing.
Aku ingat pembicaraanku dengan Sang Penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap. Karena dalam hidup, ada terang dan ada gelap. Ada perempuan dan ada lelaki.
"Gelap adalah bagian dari alam," kata Sang Penyair. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan. Atau kekelaman. "
Merinding
Narasi dalam gelap itu menggema di studio mini di bilangan Petogogan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018) lalu. Seorang tokoh lelaki berambut ikal, pendek, dan awut-awutan, diseret tak berdaya ke dalam sel penjara.
Tubuhnya ringkih dan bergetar. Wajahnya lebam dan berdarah-darah. Ia meringkuk ke sana-kemari tapi kenyamanan yang diharapkan tak tergapai.
Dari sel sebelah, Sunu membuka satu-satunya kaos yang melekat di badan. Ia mengetok sel di kanan seraya menyelipkan bajunya ke dalam. Dengan susah payah, Laut merangkak dan memungut kaos Sunu. Ia bergelung pada kehangatan yang secuil itu.
Adegan penyiksaan—yang tentunya tak seintens dalam novel—sejak awal membuat para penonton bergidik ngeri.
"Siapa pun penata riasnya, saya salut. Bikin merinding. Jadi lebih kebayang seberapa menderita dan tersiksanya para aktivis di penjara,” tutur Maria Widjaja, karyawan swasta yang gemar membaca, usai menonton film pendek Laut Bercerita.
Maria sendiri sudah lebih dulu membaca bukunya sebelum menonton film pendek sebagai teaser novel terbaru karya Leila S. Chudori ini. Setelah melihat film pendeknya, ia pun merasa semakin hanyut dalam cerita. Apa yang sebelumnya hanya sebuah bacaan dengan daya khayal yang kabur, jadi begitu nyata lewat live action garapan kolektif Cineria Films dan Yayasan Dian Sastrowardoyo itu.
Laut Bercerita mengambil latar waktu antara 1991-2007. Cerita terbagi menjadi dua sudut pandang, dari kakak-beradik Biru Laut dan Asmara Jati. Di bagian Biru Laut, cerita terangkai meliputi “Seyegan, 1991” hingga “Di Sebuah Tempat, di Dalam Kelam, 1998”, sedangkan Asmara Jati dimulai dengan “Ciputat tahun 2000” sampai “Di Depan Istana Negara, 2007”.
Seperti berkali-kali ditegaskan Leila, novel berlatar belakang sejarah tahun 1998 ini fiktif. Meski begitu, ia membenarkan bahwa beberapa adegan didasarkan pada kisah dan obrolan nyata para aktivis pra-reformasi.
Sebut saja di antaranya kisah nyata dari pemimpin redaksi The Jakarta Post, Nezar Patria; penyair Orde Baru, Wiji Thukul; dan rekan-rekan aktivis yang hilang maupun selamat, seperti Noval Alkatiri, Suyat, Wilson, Mugiyanto Sipin, Waluyo Jati, dan Budiman Sudjatmiko. Belum terhitung pula anggota keluarga korban penghilangan paksa yang menjadi narasumber utamanya.
Fiktif tapi terasa nyata. Di mata pembaca seperti Maria, fakta sejarah dalam novel ini sangat meresap. Apalagi aktualitas sejarahnya diakui Maria relevan dengan dirinya, yang sudah hidup dan punya kesadaran akan apa yang terjadi pada masa itu. Walaupun begitu, bagi mereka yang tidak merasakan sejarah kelam Indonesia pun bisa menikmati rangkaian cerita yang tak menggurui.